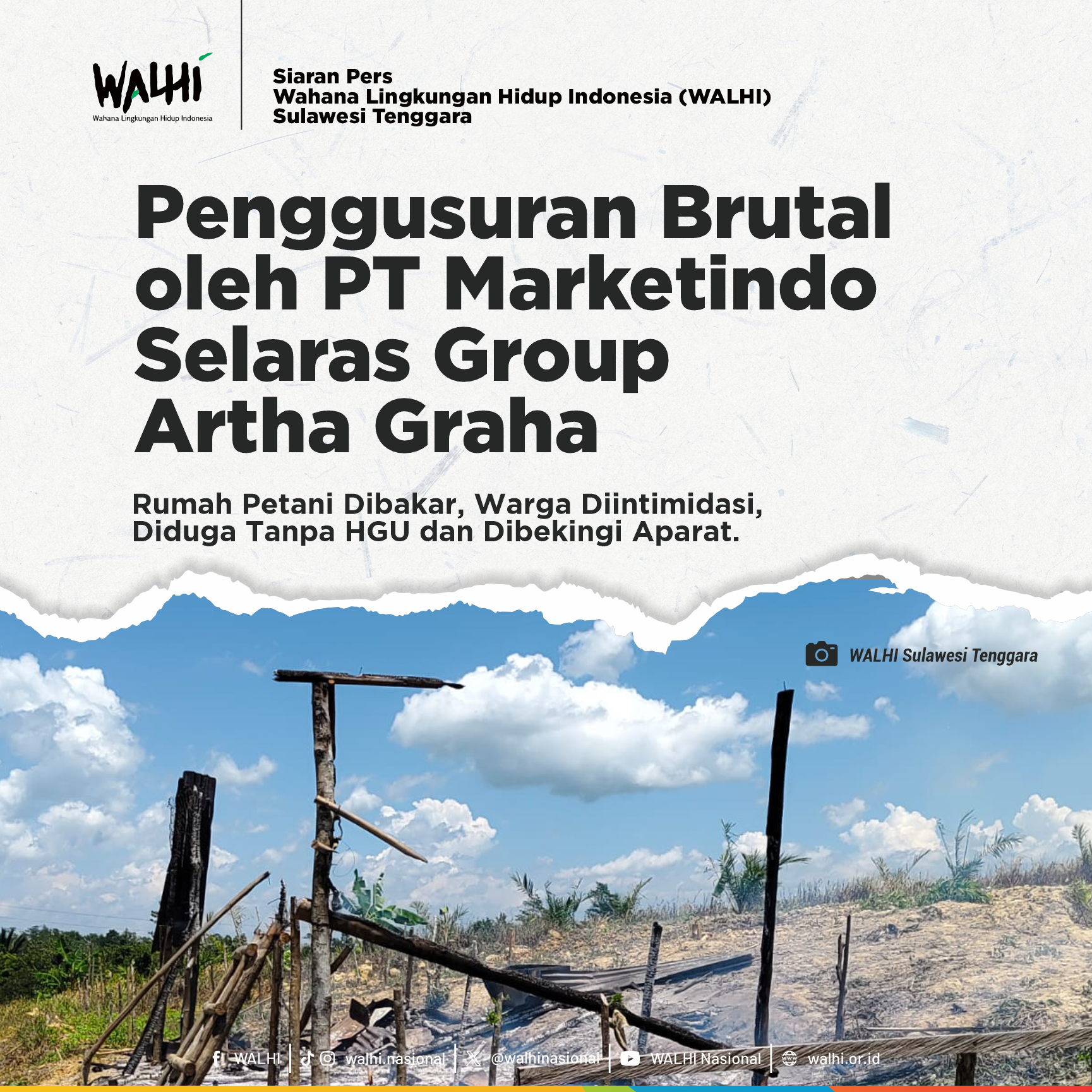Reportase diskusi
“Perempuan dan Krisis Iklim”
Seri Perdana Diskusi PEREMPUAN BANGKIT
Diskusi yang menyoal perempuan dan krisis iklim ini digelar pada tanggal 5 Februari 2020 di kantor Eksekutif Nasional WALHI Jln. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang Prapatan - Jakarta Selatan. Peserta yang hadir dalam diskusi kali ini didominasi oleh perempuan atau lebih dari setengah peserta diskusi, sedangkan sisanya adalah laki-laki termasuk narasumber dan peserta diskusi.
Digelarnya diskusi ini selain untuk menelaah relasi yang berlapis-lapis antara perempuan dengan sumber-sumber agraria yang dikelolanya, juga untuk melihat dampak multi skala yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memperkaya diskursus dan juga memberikan penyadaran ke publik luas terkait perubahan ikilm kaitannya dengan “Perempuan.”
Ada tiga orang narasumber dalam diskusi ini. Pertama, Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Iklim Global WALHI. Kedua, Dinda Anisa Yura, Ketua Solidaritas Perempuan. Ketiga, Safina Maulida (Desainer & Aktivis Iklim). Selain itu, diskusi ini juga dimoderatori oleh Giska Pramesti dari perwakilan Mahasiswa.
Yuyun Harmono dalam pemaparan materinya menyoal kenapa perubahan iklim terjadi? Pertanyaan tersebut dielaborasi dengan merujuk pada riset yang dilakukan oleh ilmuwan yang tergabung dalam IPCC pada tahun 2018. Temuan riset ini melihat dampak kenaikan suhu 1,5 derajat. Hasil riset tersebut menemukan fakta bahwa telah terjadinya kenaikan suhu rata-rata dunia sebesar 1 derajat. Bahkan, pada tahun 2030-2040 kita akan melewati batas 1,5 derajat. Negara-negara di pulau kecil kelak akan jadi climate migrant atau akan ada perpindahan tempat tinggal karena daerah mereka tenggelam akibat naiknya permukaan air laut.
Selain itu, Yuyun juga menyebutkan WALHI Sumatera Selatan dalam Catatan Akhir Tahun 2019 merilis ada dua pulau yang hilang dan ada empat pulau terancam menyusul tenggelam. Ada juga Climate Central sebuah lembaga riset di Amerika Serikat yang merilis akan ada 23 juta jiwa penduduk pesisir Indonesia yang terdampak perubahan iklim. Melihat fakta tersebut, kita sebenarnya telah sampai pada fase “krisis iklim” yang melampaui terminologi sebelumnya yakni perubahan iklim. Apa yang terjadi di Jakarta pada awal tahun 2020 merupakan salah satu dampak nyata krisis iklim. Penyedotan air tanah, privatisasi air yang berlangsung sejak 1997 menjadi salah penyebab makin parahnya dampak krisis iklim dalam bentuk banjir.
Dalam perencanaan jangka panjangnya, Pemerintah Indonesia tidak mengarahkan target pada penekanan kenaikan emisi 1,5 derajat. Kalau kita lihat dalam dokumen Nationally Determined Contributions (komitmen negara menurunkan emisi), kita tidak mengarah ke upaya mengatasi krisis iklim karena target NDC selalu naik. Emisi faktual kita dari tahun 2010-2019 sangat dinamis.
Pada tahun 2010 angka emisi faktual berada di bawah baseline data emisi NDC. Namun pada tahun 2015, emisi faktual kita jauh di atas baseline data. NDC kita harus disesuaikan dengan emisi faktual. Dalam upaya untuk melakukan penurunan emisi, kita tidak akan memenuhi target tersebut. Karena proyeksi emisi kita yang ternyata justru selalu lain, padahal seharusnya proyeksi emisi kita harus turun. Seharusnya, negara-negara berkembang diberi keleluasan dibanding negara maju karena secara historis penyumbang emisi terbesar didominasi negara maju.
Proyeksi NDC Indonesia jika kita lihat berdasarkan sektor, lebih banyak dibebankan pada sektor lahan. Sektor energi justru diberi keleluasan dan semakin meningkat emisinya.
Sementara itu, Dinda Yura yang biasa disapa “Caca” dari Solidaritas Perempuan yang lebih fokus melihat perempuan dalam relasinya dengan pengelolaan sumber-sumber produksinya mengungkapkan, ketika alam itu hancur atau rusak, perempuan akan menjadi salah satu korban pertama. Krisis iklim yang mengakibatkan gagal panen dan krisis air membawa beban ganda pada perempuan. Selain itu, perubahan iklim berimplikasi pada terjadinya alih profesi pada perempuan. Pengetahuan lokal untuk mengeringkan ikan, memuliakan benih yang dimiliki perempuan berpotensi hilang karena perubahan iklim.
Dalam kasus climate migrant atau misalnya dalam konteks bencana, penyintas perempuan memiliki kerentanan tinggi. Studi pasca bencana di Palu, Sigi dan Donggala menunjukkan tren kenaikan pernikahan dini. Selain itu, studi kasus di Kalimantan pasca program REDD+, sebuah proyek carbon trading berkedok pemulihan ekosistem gambut. Perempuan justru terdampak dari proyek ini: (1) Pembatasan akses perempuan dan masyarakat ke dalam hutan; (2) Menghilangkan sumber kehidupan perempuan pada tanaman sayur, ikan dan rotan; (3) Rentan terjadi kriminalisasi karena pembatasan akses kelola.
Selama ini perempuan dan komunitasnya konsisten dalam pelestarian lingkungan. Kegagalan proyek kehutanan di Kalimantan Tengah bisa dilihat dari masih terjadinya karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Isu iklim dalam analisis interseksional berelasi erat dengan konflik kelas. Ketimpangan kelas terjadi juga dalam krisis iklim seperti negara maju dengan negara berkembang. Negara maju (industri) memanfaatkan negara berkembang untuk menekan emisi, sedangkan mereka masih tetap menghasilkan emisi yang tinggi.
Lebih lanjut menurut Caca, gerakan perempuan bisa melakukan intervensi untuk memasukkan Gender Action Plan dalam perencanaan kebijakan iklim. Perlu juga memperkuat inisiatif perempuan dalam komunitas untuk menyadari masalah krisis iklim. Hal tersebut misalnya dilakukan oleh Solidaritas Perempuan di Kalimantan Tengah menyikapi proyek KFPC (Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan). Krisis iklim bukan masalah kelas menengah, tetapi semua elemen masyarakat.
Kenapa kita mendorong climate justice? Karena masalah iklim itu mencakup masalah keadilan antara negara maju dengan negara berkembang, antara kaya dengan miskin. Perjuangan keadilan iklim adalah bagian dari perjuangan gerakan feminisme. Pengalaman pribadi saat bergerak bersama feminis internasional, kami melakukan demonstrasi bersama menuntut keadilan iklim.
Agenda ke depan penting untuk merebut agenda penanganan krisis iklim. Bicara krisis iklim jangan berhenti pada tanggung jawab individu seperti gaya hidup tidak membuang dan menggunakan sampah palstik sekali pakai. Kita harus membajak balik agenda tersembunyi yang menambah beban perempuan. Masalah iklim adalah masalah ideologi, interseksional dan lintas isu. Perlu mendukung perlawanan di akar rumput. Misalnya di tapak-tapak penolak tambang batu bara dll.
Safina Maulida yang menjadi narasumber terkahir dari diskusi ini, melihat masalah perubahan iklim kaitannya dengan perempuan fokus mengkritik konsep-konsep yang mengabaikan keseimbangan ekologi dan manusia dan lebih mengutamakan kepentingan ekeonomi semata. Konsep tersebut menurut Safina yang digunakan oleh pemerintah saat ini.
Sebagaimana tujuan dalam diskusi ini adalah untuk berbagi pengetahuan terkait diskursus perempuan dan perubahan iklim, panitia sengaja memberi waktu untuk peserta diskusi untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagian besar adalah telaah atas informasi yang dimilliki dikemas dengan konteks yang mudah dipahami oleh generasi masa kini. Seperti wajah penulisan yang populer saat disajikan ke publik. Selain itu, ada juga eksplorasi pada metode-metode baru kaitannya dengan gerakan lingkungan hidup masa kini.
Rencana tindak lanjut dari diskusi ini adalah terus meresonansi diskusi baik di dalam kelompok diskusi maupun masyarakat luas. Diskusi ini adalah diskusi berseri dengan nama “Perempuan Bangkit.”[]