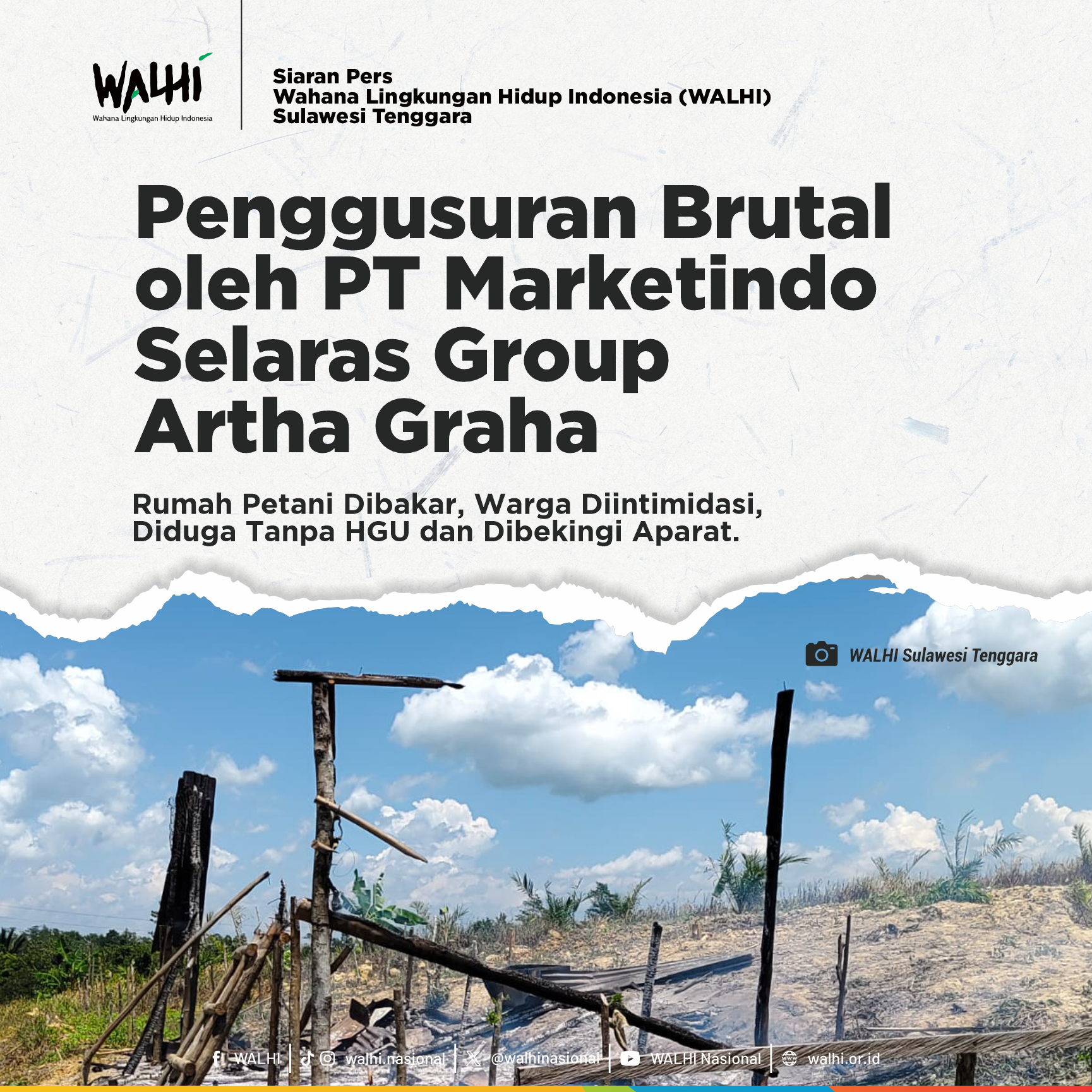KERTAS POSISI WALHI
Legally Binding Treaty on Business and Human Rights: “MENDESAK TANGGUNGGUGAT KORPORASI & TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEJAHATAN EKOSIDA”
Pengantar
Korporasi seperti tak tersentuh hukum. Penegakan hukum oleh Negara dalam hal pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya tidak pernah tuntas. Bahkan, pengaruh korporasi dalam sistem hukum dan politik ikut berkontribusi terhadap hilangnya tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia. Faktanya sejarah panjang telah membuktikan sulitnya mengontrol korporasi serta upaya meminta pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya. Sejak tahun 1970an komunitas internasional di PBB telah memulai upaya ini.
Berawal dari dorongan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 (Group of 77/G77), pada tahun 1974 di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC) mengadopsi program tentang ‘Pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas korporasi transnasional (transnational corporations/TNCs)’. Pengadopsian inilah yang mendorong terbentuknya United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) dan Intergovernmental Commission on Transnational Corporations ICTC). Dua lembaga ini dimandatkan untuk membentuk sebuah Statuta hukum internasional untuk mengontrol TNCs. Namun, hingga tahun 1994 Statuta tersebut tidak pernah diadopsi, dan pada akhirnya kedua lembaga tersebut diganti dengan UN Conference on Trade and Investment (UNCTAD).
Upaya mengontrol korporasi terus berlanjut dan pada 1998 di bawah UN Sub-Commission on the Promotion and protection of Human Rights dibentuklah sebuah Kelompok Kerja (Working Group) untuk menyusun sebuah standar norma untuk TNCs (Draft Norms). Namun, pada tahun 2004 Commission on Human Rights menolak dan menyatakan draft tersebut tidak memiliki kedudukan hukum. Pada akhirnya sub-komisi diinstruksikan untuk tidak terlibat dalam melakukan monitoring TNCs dan mengalihkan tugas tersebut kepada organ PBB lainnya, yaitu Special Representative of the Secretary General.
Akibat penolakan ini, maka pada 2005 Sekjend PBB saat itu, Kofi Annan, menugaskan John Ruggie, seorang Special Rapporteur dalam bidang bisnis dan HAM yang juga sebagai penyusun UN Global Compact, untuk kembali mengkaji isu ini. Kajian Ruggie ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan dimana tahun 2011 UN Human Rights Council mengadopsi The Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).
Penegakan Bisnis dan HAM Dengan Aturan Mengikat
Dalam perkembangannya, banyak pihak yang merasa penerapan UNGP masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini karena UNGP ini dianggap tumpul dalam penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM oleh korporasi. Lemahnya mekanisme pemulihan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pada akhirnya kembali mendesak UNHRC agar membuat sebuah instrument hukum yang mengikat, karena selama ini pengadopsian prinsip-prinsip Bisnis dan HAM penerapannya hanya bersifat sukarela sehingga sulit untuk menegakkan pertanggung jawaban korporasi. Di Indonesia, acap kali korporasi merasa telah cukup memenuhi tanggungjawabnya melalui program CSR (corporate social responsibility), yang justru menjadi modus baru “pembungkaman” suara kritis masyarakat yang terkena dampak.
Pada November 2013, muncul satu proposal dari Ecuador dan Afrika Selatan untuk mendorong inisiatif pembentukan open-ended Intergovernmental Working Group (IGWG) untuk membahas pembentukan Instrumen hukum yang mengikat untuk mengontrol TNCs dalam menegakan HAM dan membuat sebuah mekanisme remedy yang efektif berikut sanksi yang tegas dan mengikat korporasi. Proposal ini kemudian didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam The African Group, The Arabic Group, Pakistan, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, dan Peru.
Pada Juni 2014, dalam Sesi ke 26, UNHRC di Jenewa mengadopsi proposal Ecuador dan Afrika Selatan menjadi Resolusi UNHRC 26/9 yang diperkuat dengan 20 negara yang menghendaki proses pembentukan IGWG on TNCs yakni: Algeria, Benin, Burkina Faso, China, Congo, Cote d’Ivoire, Namibia, Ethiopia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Morocco, Pakistan, Filipina, Rusia, Africa Selatan, Venezuela, Vietnam. Namun, pertentangan cukup keras muncul dari 14 negara yang menyatakan menolak atau against seperti: Austria, Chech Republic, Estonia, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Montenegro, Korea Selatan, Romania, Macedonia, UK, dan USA. Sedangkan 13 negara abstain yakni: Argentina, Botswana, Brazil, Chile, Costa Rica, Gabon, Kuwait, Maldives, Mexico, Peru, Saudi Arabia, Sierra Leone, United Emirates Arab.
Sejak itu, IGWG telah bersidang sebanyak 4 (empat) kali di Jenewa (2015-2018) yang pada akhirnya pada sesi sidang ke-4 IGWG, yakni Oktober 2018, telah menghasilkan zero draft text dari legally binding treaty yang diharapkan dapat dibahas pada putaran sidang berikutnya.
Legally Binding Treaty: “Menutup Celah Regulasi”
Proposal mengenai kerangka hukum mengikat dalam hukum HAM Internasional tentang bisnis dan HAM didorong oleh pemikiran dari sejumlah besar negara berkembang dan kelompok masyarakat sipil Internasional yang mempertanyakan efektivitas UNGP dalam menyelesaikan pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional. Pada September 2013, sebuah pernyataan bersama yang mendukung perjanjian internasional tentang bisnis dan hak asasi manusia dirancang dan dikeluarkan oleh Ekuador.
Dalam statement tersebut disebutkan bahwa prinsip-prinsip dan mekanisme yang tertuang di dalam UNGP gagal menangani dengan baik masalah akuntabilitas Perusahaan Transnasional di seluruh dunia, dan tidak adanya pemulihan hukum yang memadai bagi para korban. Sehingga pembentukan instrumen bisnis dan HAM internasional yang mengikat secara hukum akan digunakan untuk mengklarifikasi kewajiban perusahaan transnasional di bidang hak asasi manusia, dan menyediakan mekanisme pemulihan hak yang efektif bagi para korban dalam kasus dimana yurisdiksi domestik gagal meminta pertanggung-jawaban perusahaan-perusahaan tersebut secara efektif.
Kurangnya mekanisme yang mengikat pada aktivitas perusahaan meninggalkan celah regulasi (regulatory gap), karena mekanisme nasional yang ada dalam banyak kasus terbukti tidak cukup untuk menangani situasi yang timbul dari usaha bisnis transnasional secara memadai. Di sisi lain, UNGP didasarkan pada prinsip negara sebagai penjaga utama hak asasi manusia, menempatkan fokus pada penguatan mekanisme hukum nasional bagi negara untuk mengatur kegiatan perusahaan di wilayah mereka dengan tanggung jawab yang tidak mengikat bagi perusahaan mematuhinya.
Masalah kembali muncul ketika keterbatasan yurisdiksi hukum nasional tidak dapat menggapai struktur korporasi yang kompleks, yang memungkinkan mereka menghindar dari pertanggungjawaban dalam banyak kasus. Grup perusahaan yang berisi perusahaan induk, anak perusahaan, afiliasi, usaha patungan, rantai pasokan, dan lainnya, biasanya diperlakukan sebagai entitas yang terpisah, meskipun sering kali terdapat hubungan yang sangat erat dalam grup. Hal ini menyebabkan grup perusahaan dapat melindungi diri mereka sendiri dari tanggung jawab dengan bisnis berisiko dengan memanfaatkan anak perusahaan, yang mengandung kerusakan pada cabang perusahaan tertentu. Bahkan, menjadi lebih rumit ketika penindakan hukum harus melintasi perbatasan, terutama jika rantai kepemilikan melewati sejumlah anak perusahaan yang berdomisili di negara bagian yang berbeda. Belum lagi keterkaitan dengan sektor pendanaan, termasuk lembaga keuangan internasional (IFIs) yang menyalurkan dananya untuk membiayai industri ekstraktive.
Oleh karena itu, aspek territorial lintas batas (extraterritorial) menjadi sangat penting di dalam upaya penegakan hukum terhadap korporasi multinasional. Aspek extraterritorial masih menjadi perdebatan di dalam hukum ham internasional. Pihak SRSG yang mengembangkan UNGPs menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk mengatur kegiatan ekstrateritorial, tetapi tidak ada larangan untuk melakukannya. Pihak lainnya menyatakan adanya kewajiban implisit pada negara untuk mengatur kegiatan ekstrateritorial, hingga korban pelanggaran hak asasi manusia perusahaan yang dibawa ke dalam yurisdiksi negara asal perusahaan pelanggar, hingga tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia lintas negara yang dikaitkan dengan negara asal perusahaan. Tetapi, hukum HAM internasional secara jelas menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melindungi tidak terbatas pada kasus-kasus yang ada di wilayah mereka saja.
Masalah lain adalah kurangnya kerja sama lintas batas antara sistem hukum negara terkait akses terhadap pemulihan korban. Sebagaimana disebutkan mengenai adanya celah hukum dalam hukum hak asasi manusia internasional dapat dikatakan sebagai fakta yang tidak terbantahkan, dan tantangan sebenarnya adalah untuk mencapai konsensus global tentang cara menutup kesenjangan itu. Sehingga ada kebutuhan kuat untuk kerja sama internasional untuk secara efektif memberikan pemulihan bagi para korban, di mana pun mereka tinggal. Untuk itulah kenapa kita butuh legally binding treaty untuk menutup kesenjangan hukum tersebut.
Posisi Terhadap “Zero Draft” LBI
WALHI/Friends of the Earth Indonesia merupakan anggota dari Indonesia Focal Point for legally Binding Treaty yang juga adalah bagian dari The Global Campaign to Dismantle Corporate Power, yaitu jaringan yang terdiri lebih dari 200 gerakan sosial, organisasi dan komunitas yang terkena dampak dan menentang perampasan tanah, penambangan ekstraktif, upah eksploitatif dan perusakan lingkungan dari perusahaan transnasional (TNC) di berbagai kawasan global terutama di Afrika, Asia dan Amerika Latin.
Dalam sesi ke-4 pembahasan legally binding treaty di Jenewa Oktober 2018 yang lalu telah menghasilkan Zero draft text treaty. Namun, draft teks ini masih perlu dikritisi dan diintervensi dalam pembahasannya di Jenewa guna menjawab persoalan yang dihadapi oleh komunitas terdampak dan human rights defender yang jauh dari rasa keadilan. Terlebih bagi Indonesia, dimana angka kekerasan dan kriminalisasi terus dialami oleh masyarakat maupun aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya.
Untuk itu, WALHI kembali menekankan pentingnya memberikan intervensi dalam proses pembahasan legally binding treaty on business and human rights baik pada level nasional maupun internasional, khususnya yang terkait dengan penajaman aspek pengaturan isu lingkungan hidup. Di bawah ini adalah isu-isu penting yang harus menjadi posisi tawar kelompok masyarakat sipil di dalam perundingan LBI:
- Ruang Lingkup LBI
WALHI mendesak agar ruang lingkup aturan dalam legally binding treaty perlu mempertegas dan mengakui tindakan Ecocide atau Ekosida sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM serius atas aktivitas bisnis khususnya yang bersifat transnasional (Lihat Box 1). Dalam definisinya, Ekosida adalah tindakan terencana langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi dasar ekologi dari sebuah tata kehidupan semua makhluk di dalamnya. Oleh karena itu, legally binding treaty perlu memasukan unsur-unsur hukum mengenai Ecocide, yaitu:
- Terjadi kerusakan yang luas;
- Kerusakan atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu;
- Apakah oleh seorang manusia atau oleh penyebab lain, sedemikian rupa; dan
- Kenikmatan damai oleh penduduk wilayah yang telah berkurang parah.
Penegasan terhadap pelanggaran HAM akibat tindakan Ekosida menjadi sangat penting, karena dari sekian banyak kasus di sektor ekstraktif Indonesia, hampir semuanya menimbulkan akibat yang menghancurkan dan memusnahkan eksistensi dasar ekologi kehidupan makhluk hidup.
Misalnya, kasus Lapindo Brantas hingga saat ini telah menenggelamkan 9 (sembilan) desa di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Jumlah warga yang sebelumnya bermukim di desa-desa sekitar lokasi semburan yang terpaksa dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa dan tak kurang 25.000 jiwa mengungsi. Aliran lumpur yang dipaksa dibuang ke sungai Porong telah berdampak sangat serius bagi kehidupan manusia. Tercatat ribuan hektar tambak milik penduduk gagal panen karena tercemar oleh lumpur yang dibuang ke Sungai Porong, termasuk pencemaran air bersih untuk warga yang bersumber dari sumur, pencemaran sungai dan tambak milik warga, dan kandungan gas yang menyesakkan dan mengandung racun yang sangat berbahaya. Komnas HAM dalam kasus lumpur Lapindo menyimpulkan bahwa ada 15 point atau kriteria pelanggaran HAM, diantaranya hak untuk hidup. Hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas kesehatan, hak atas pangan. Dan pada ringkasan eksekutif Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat. Tim Adhoc juga menyimpulkan adanya bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (patern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam kasus lumpur panas Lapindo.
Dalam kasus kebakaran hutan, Ekosida dapat berlaku. Hal ini karena kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut berdampak terhadap hancurnya dan musnahnya ekosistem makhluk hidup. Selain karena faktor iklim, faktor manusia dan kebijakan memegang peranan yang sangat besar terkait kejadian kebakaran hutan di Indonesia secara umum dan khususnya di beberapa provinsi di Kalimantan dan Sumatera yang puluhan tahun terpapar asap. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu di Kalimantan dan Sumatera berlangsung sangat masif, mengakibatkan dampak kerugian yang tidak sedikit naik dilihat dari kerugian ekologis, ekonomi hingga sosial budaya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK (Si Pongi) luasan lahan yang terbakar pada tahun 2015 mencapai 2,61 juta hektar dan di Kalimantan Tengah mencapai 122. 882, 90 hektar dan terluas di Indonesia[1]. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peristiwa kebakaran hutan lahan dan kabut asap pada rentang waktu Juni – Oktober 2015 menyebutkan sebanyak 24 orang meninggal, lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA. 70% diantaranya adalah anak-anak. 12 orang anak-anak meninggal dunia akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan. 4 balita di Kalteng, 3 orang anak di Jambi, 1 orang anak di Kalbar, 3 orang anak di Riau dan 1 orang anak di Sumsel.
Selain rusaknya lahan karena terbakar, kabut asap yang dihasilkan bahkan sampai bisa di ekspor ke negara tetangga. Karbon dioksida dan gas buangan lainnya yang diproduksi akibat proses kebakaran hutan dan lahan menempatkan Indonesia sebagai penyumbang deposit Gas Rumah Kaca terbesar ke-3 setelah Amerika dan Cina, sehingga bencana iklim (climate disater) yang terjadi juga merupakan sumbangsih yang ditimbukan oleh aktivitas pembakaran hutan dan lahan.
|
Box 1 EKOSIDA
Proposal untuk kejahatan ekosida diajukan ke PBB oleh pihak swasta. Pada bulan Maret 2010, "pengacara bumi" dari Inggris, Polly Higgins, mengajukan proposal untuk melakukan amandemen Statuta Roma kepada PBB. Ia mengusulkan bahwa "ecocide" perlu diakui secara hukum sebagai Kejahatan internasional kelima melawan perdamaian. Statuta Roma saat ini mengakui empat kejahatan terhadap perdamaian, yaitu: genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan kejahatan agresi. Setiap kejahatan ini mempengaruhi korban manusia.
Polly Higgins mendefinisikan ekosida sebagai "kehancuran yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah, baik oleh agen manusia atau oleh sebab lain, sedemikian rupa sehingga kenikmatan damai oleh penduduk di wilayah itu telah sangat berkurang. Beberapa contoh untuk ekosida yang dimaksud Higgins seperti, deforestasi, penangkapan ikan berlebihan, penambangan dan ekstraksi pasir tar. Hal-hal ini terjadi di seluruh dunia setiap hari - dan belum dapat dihukum berdasarkan hukum internasional. Usulan Higgins dapat dilihat sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang, perusahaan, dan negara atas kehancuran terhadap bumi.
Pada Oktober 2012, sejumlah pakar berkumpul di acara konferensi internasional mengenai “Kejahatan Lingkungan: Ancaman Saat Ini dan Ke Depan”, diadakan di Markas Besar Organisasi Pangan dan Pertanian PBB di Roma yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Kejahatan dan Keadilan Antar Wilayah PBB (UNICRI) bekerja sama dengan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (Italia). Konferensi tersebut mengakui bahwa kejahatan lingkungan hidup adalah bentuk baru penting kejahatan transnasional terorganisir yang membutuhkan respons yang lebih besar. Salah satu hasilnya adalah bahwa UNEP dan UNICRI mengepalai sebuah studi tentang definisi kejahatan lingkungan hidup, kejahatan lingkungan hidup baru dan mempertimbangkan sejarah menjadikan ecocide sebagai kejahatan internasional sekali lagi.
|
- Yurisdiksi
Zero draft legally binding treaty harus mengatur mengenai pertanggung jawaban korporasi yang memiliki struktur kompleks hingga struktur supply chain serta peran lembaga pembiayaan investasi. WALHI mendesak agar aspek-aspek ini menjadi perhatian penting dalam perundingan di Jenewa. Hal ini mengingat instrument hukum nasional Indonesia, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup; belum dapat menyentuh pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi transnasional dan rantai pasokan yang memungkinkan bisnis mereka tetap berjalan, termasuk sektor pendanaan seperti bank yang selalu mendukung pendanaan industri ekstraktif.
Memasukan konteks rantai pasok di dalam aspek yuridiksi ini menjadi penting sehingga memungkinkan komunitas terdampak dan human rights defender untuk mengakses keadilan di pengadilan negara dimana kerugian terjadi atau dimana TNCs dan perusahaan rantai pasoknya berdomisili untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maka prinsip ekstrateritorial menjadi amat penting untuk diterapkan.
- Liability
Zero draft mendorong agar Negara harus memastikan melalui hukum nasionalnya bahwa orang perseorangan dan badan hukum dapat dipidana secara pidana, perdata atau secara administratif untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks kegiatan bisnis yang bersifat transnasional.[2] Tanggung jawab tersebut harus dikenai sanksi pidana dan non-pidana yang efektif, proporsional, termasuk sanksi moneter.
Di bawah Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah diberlakukan sanksi pidana kepada para perusak lingkungan. Pasal-pasal mengenai ketentuan pidana ini pada akhirnya hanya menjadi secarik kertas yang tak bermakna ketika berhadapan dengan para pemilik modal yang di-backing oleh pihak penguasa. Pada akhirnya dengan dasar pembangunan jugalah lingkungan hidup dirusak. Oleh karena itu, WALHI menilai perlu mendesakan sebuah kerangka hukum pidana di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga dapat secara efektif menghukum pelaku kejahatan lingkungan. Ide mengenai Ecocide sebagai kejahatan internasional luar biasa bisa menjadi salah satu kerangka hukum internasional baru yang dapat didorong penerapannya di dalam LBI ini.
Walaupun kejahatan Ekosida belum diakui secara tegas keberadaannya dalam sebuah instrument hukum internasional, paling tidak baseline mengenai Ekosida sudah bisa menjadi dasar membuka kembali ruang-ruang diskusi di Jenewa khususnya dalam kerangka hukum pidana internasional. Sebagai sebuah konsep, kejahatan Ekosida patut untuk diuji kelayakannya. Pengalaman di Inggris pada tahun 2011 bisa menjadi sebuah referensi untuk mengembalikan ide mengenai pengadilan untuk Ekosida di level internasional.
Sebagai informasi, Mahkamah Agung Inggris pernah melakukan persidangan semu (Mock Trial) untuk menguji bagaimana Ekosida dapat diterapkan di dalam hukum pidana Inggris. Pada 30 September 2011, Para petinggi dari dua perusahaan multinasional terbesar di dunia, dari Global Petroleum Company (GPC) dan Glamis Group, ‘dihukum’ akibat tindak pidana Ekosida oleh juri di Mahkamah Agung (Inggris) karena menghancurkan ekosistem global terkait dengan ekstraksi minyak di Kanada, sementara satu dibebaskan dari tuduhan terkait tumpahan Teluk. Selain itu, International Criminal Court (ICC) memasukkan proposal kejahatan ecocide sebagai kejahatan ke-5 terhadap siapapun dan tidak adanya impunitas bagi siapapun.
Semua upaya advokasi yang dilakukan di tingkat nasional dan internasional ini sebagai upaya dari organisasi masyarakat sipil untuk memutus rantai impunitas korporasi. Serta memaksa negara menjalankan kewajiban Konstitusinya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. ****
Referensi:
Kertas Posisi Indonesia Focal Point 2015
The Global Campaign Comments on Zero Draft Text https://www.stopcorporateimpunity.org/call-to-international-action/
[1]http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran
[2] Dalam lingkup ini, termasuk di dalamnya perusahaan nasional yang menjalankan praktik bisnis yang bersifat trans nasional atau masuk dalam lingkar supply chain, seperti PT. Semen Indonesia